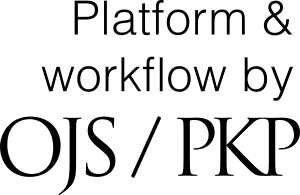Aspek Sosial Budaya dalam Cerita Rakyat Enyeng di Desa Cipancar
DOI:
https://doi.org/10.33603/deiksis.v5i1.838Abstract
ABSTRAK
Â
Semakin derasnya arus teknologi informasi yang membuat cerita rakyat menghadapi tantangan untuk tetap tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kurang menariknya penyajian materi cerita rakyat di sekolah membuat cerita rakyat semakin terabaikan. Untuk mendongkrak hal tersebut maka perlu adanya analisis terhadap karya sastra, agar karya sastra tersebut dapat digunakan sebagai pemilihan bahan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat aspek sosial dan budaya. Aspek sosial yang paling banyak muncul dalam cerita rakyat “Enyeng†adalah karakteristik masyarakat pedesaan yang mencerminkan jika diberi janji akan selalu diingat dengan frekuensi 3 buah. Hal ini membuktikan bahwa warga desa Cipancar sangat memegang teguh janji dan amanah dari leluhurnya. Sedangkan nilai budaya yang paling banyak muncul dalam cerita rakyat “Enyeng†adalah sistem religi dengan frekuensi 3 buah. Ini membuktikan bahwa mayarakat desa Cipancar masih memegang teguh ajaran tentang apa yang harus dipercayai, diyakini dan diimani oleh setiap orang Islam. Tradisi lisan untuk mengganti nama hewan kucing/ucing dengan ènyèng/emèng/mèong merupakan hasil budaya dari generasi-kegenerasi, kemudian mereka memegang teguh pada keyakinannya yang dikukuhkan oleh legenda dan mitos dalam bentuk tradisi lisan. Walaupun mereka menerima budaya luar yang datang dan mereka mengikuti kemajuan/budaya modern, namun mereka tetap memegang teguh keyakinannya, dimanapun mereka berada atau sekalipun dalam perantauan.
Â
Kata Kunci: aspek sosial budaya, cerita rakyat, enyeng Cipancar
References
Aminuddin. (2009). Pengantar Apresiasi Karya Sastra. Bandung Sinar Baru Algesindo.
Danandjaja, J. (2007). Folklor Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Djajasudarma, F. T. (1999). Semantik 2: Pemahaman Ilmu Makna. Bandung: PT Refika Aditama.
Koentjaraningrat. (2000). Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Ratna, N. K. (2011). Antropologi Sastra: Peranan Unsur-unsur Kebudayaan dalam Proses Kreatif. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
Saini, K.M. (1993). Cerita Rakyat Dari Jawa Barat. Jakarta: Grasindo.
Stanton, R. (2012). Teori Fiksi Robert Stanton. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Teeuw. (1984). Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra. Jakarta: Erlangga.
Sudjiman, P. (1988). Memahami Cerita Rekaan. Jakarta : Pustaka Jaya.
Wellek, R, dan Warren, A. (1989). Teori Kesusastraan. Diterjemahkan oleh Melani Budianta. Jakarta: Gramedia.
Downloads
Published
Issue
Section
Citation Check
License
Penulis yang menerbitkan karyanya ke jurnal ini setuju dengan persyaratan berikut:
Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama, dengan karya yang secara serentak dilisensikan di bawah Lisensi: Creative Commons Attribution - Share Alike 4.0 Internasional License yang memungkinkan orang lain membagikan karya dengan pengakuan penerbitan awal dan kepenulisan karya di jurnal ini.